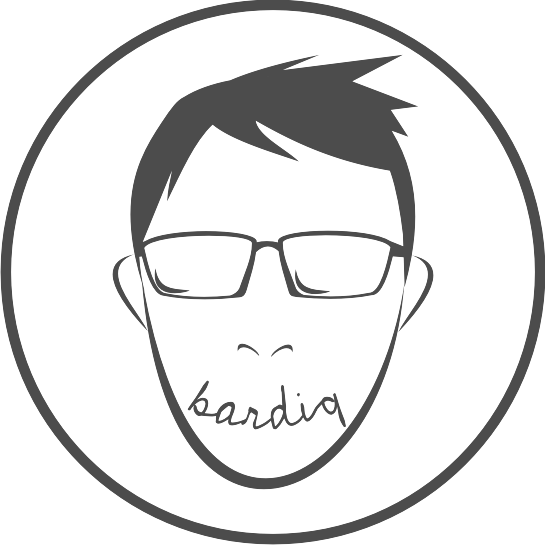25 September 2017 – Leh, Khardung La, Turtuk
Seperti pagi-pagi di Ladakh sebelumnya, saya bangun lebih cepat dari alarm saya. Karena udah bolak balik ganti posisi tidur, dimeremin terus biar bablas tidur lagi, tapi ternyata tetep gagal, jadi saya putuskan untuk bangkit dan mandi. Yes, penginapan kami, Silver Line, menyediakan air panas 24 jam. Walopun ada yang bikin was was: itu colokan listrik di kamar mandi dipasang deket amat sama shower. Pas saya mandi, air ke mana mana, ngeri juga kalo kesetrum.
Karena tau kalo Leh di pagi hari itu masih sepi, masih banyak toko yang tutup, jadi kami minta penginapan buat nyediain sarapan. Walopun mereka cuma nyediain corn flakes sama susu. Saya minta dicariin pisang juga. Silver Line sebenernya menyediakan menu dengan daftar makanan yang lumayan, tapi mereka tidak punya stok bahan makanan. Jadi, apa yang dipesan oleh tamu, mereka bakal belanja terlebih dulu. Jadi kayak makan malam kami sebelumnya, perlu nunggu sekitar satu jam untuk disiapin makan. Jadi, pesanlah jangan terlalu mepet.
Sebelum berangkat, kami puas puasin dulu koneksi WiFi di Silver Line sebelum berhari-hari ke depan nggak dapet sinyal internet. Termasuk mau ngabarin si Naya, nggak bisa ikut ketemuan nanti malem di Summer Harvest. Satu satunya cara buat ngabarin: DM Instagram. Yah, walopun kecil kemungkinan dia mau baca DM Instagram dari saya.
Jam 9 kurang kami diminta untuk sudah stand by di Ancient Tracks, karena trip akan berangkat jam 10 teng. Biar nggak terlalu molor, karena dari Ancient Tracks kami harusjemput Gal Gadot dan temennya dulu sebelum memulai trip.
Saat check out dari penginapan, pemilik Silver Line, Dorje, menanyakan kapan kami akan kembali ke Leh. Kami jawab belum tau, mungkin dua atau tiga hari lagi. Kami tau Dorje mengharapkan kami bakal nginap lagi di Silver Line. Tapi saat itu kami mau nyobain ke salah satu penginapan yang sudah kami booking (tapi belum kami bayar), yang banyak juga yang ngerekomendasiin, Oriental Hotel. Lalu Dorje bilang, “If you stay here again, I will give you discount.” Kami ter-pause sejenak. “How much?” Saya tanya balik ke Dorje. “Big Discount.” Kami langsung senyum senyum sendiri.
Kami mengumpulkan pakaian-pakaian kotor selama perjalanan yang rencananya akan kami masukin penatu (baru tau kalo menurut KBBI, yang baku adalah penatu, bukan binatu). Kami nemu tempat laundryan (ujung-ujungnya pake ‘tempat laundryan’) di deket Ancient Tracks. Yang menjaga tempat laundryan adalah seorang perempuan Ladakhi yang ramah tapi tidak lancar berbahasa Inggris. Satu kilonya Rs. 90, atau sekitar 18 ribu Rupiah. Jauh lebih murah ketimbang tempat laundryan yang kami temuin hari sebelumnya, bukan Ladakhi (if you know what I mean) dan mematok harga Rs. 150 untuk satu kilonya. Di Ladakh, penggunaan tas kresek adalah dilarang, jadi jangan masukan pakaian kotor kamu ke dalam tas kresek ya. Saya sempet belanja makanan, dan dapat sejenis tas dari kain yang memang wajar dipakai di Ladakh. Jadi saya simpan tas tas tersebut.
Kami sampai di Ancient Tracks jam 9 kurang, dan kantor masih sepi. Baru ada satu orang yang duduk di belakang monitor menyapa kami. Kesang belum nampak, kursinya masih kosong. Karena segala urusan pembayaran, adminsitrasi, dan segala tetek bengeknya udah terlanjur sama Kesang, jadi Mbak Mbak yang kami belum tanya namanya mempersilakan kami duduk dulu. Karena saya masih laper, jadi saya mau keluar sebentar cari makanan.
Ngomong-ngomong, kenapa ya namanya ‘tetek bengek’. Kalo menurut KBBI, dua kata itu punya arti sendiri-sendiri. ‘Tetek: n susu; payudara’, dan ‘Bengek: a sesak napas’ Kalo digabung? Payudara siapa yang sesak napas? No, bukan bermaksud porno. Ah otak situ aja yang ngeres kalo saya bahas tetek terus jadi porno. Tapi untungnya, KBBI juga mencantumkan tetek bengek sebagai bahasa baku, ‘Tetek bengek: n remeh cemeh, remeh temeh’.
Lumayan susah cari sarapan di Leh sebelum jam 9. Masih pada tutup, harus masuk ke gang-gang kecil baru saya nemu tempat makan khas Punjab. Saya pesan Aloo Paratha dan Chana. Aloo Paratha ini seperti Chapati, namun menurut saya rasanya lebih gurih, lalu disandingkan dengan Chana. Chana ini saya nggak ngerti dibuat dari apa, yang jelas karena saya minta untuk take away, Chana dibungkus dalam plastik terpisah karena banyak kuahnya. Rasanya agak pedes dan khas makanan Punjab, rempah-rempahnya kuat banget.
Jam 9.30 dan Kesang belum juga datang. Nggak lama, Mbak Mbak yang duduk di meja sebelah Kesang memperkenalkan kami dengan satu laki-laki yang dari tadi memang saya lihat udah mondar-mandiri di depan kantor Ancient Tracks. Dia adalah taxi driver kami, Gyal. Gyal adalah driver yang handal dan hobi banget ngelakson. Memang sih, jalanan yang kami tempuh memang berliku dan wajib ngelakson kalau ketemu tikungan tajam. Tapi pas nyalip dikit juga, ngelakson mulu. Sampe pas hari ketiga kami pulang, akinya mulai kering kali ya, suara klasksonnya mulai fals. Tapi, Gyal sangat pendiam. Jarang ngajak ngobrol, dan kalo ditanya ngejawab seadanya. Mungkin karena dia nggak lancar berbahasa Inggris juga, jadi kadang komunikasi kami juga pakai bahasa isyarat.
Jam 10 kurang kami berangkat dari Ancient Tracks, jemput Rina dan temannya dulu di salah satu penginapan, Mentokling Guest House and Apple Garden Restaurant. Salah satu penginapan yang banyak direkomendasiin dan rame. Dari agoda pemesanan harus jauh-jauh hari kalo mau kebagian kamar. Pas nungguin Rina dan temennya, saya sempet ngobrol-ngobrol sama yang jaga penginapan. Penginapan mereka sering nerima tamu orang Indonesia dan nemenin mereka roadtrip pake moge, beberapa nama dia sebut termasuk a chef with a lot of tattoss in his hands, kata dia karena lupa siapa nama si chef ini.
Ada sekitar 20 menit kami nungguin Rina dan temennya siap-siap. Baru akhirnya mereka muncul. Sepasang laki-laki dan perempuan keluar dari penginapan. Rina and Yosi. Mereka turis asal Israel yang sudah berkunjung di Ladakh sekitar tiga hari lebih dulu dari kami. Usia mereka sekitar 50an. Hey, mana Gal Gadot saya? Dalam hati sedikit nyalahin Kesang yang terlalu mempromosikan trip bareng Rina.
Lalu trip kami pun dimulai. Leh macet pagi itu, Gyal harus lumayan muter buat menghindari macet yang lebih parah lagi. Lama kelamaan kami mulai menjauhi Leh, menaiki tepian gunung-gunung batu. Leh makin lama makin mengecil, ada satu titik yang sempat saya simpan lokasinya karena berniat pas keliling Leh, buat mampir ke tempat itu. Leh nampak cantik banget dari sini. Kota terbesar di Ladakh ini terlihat membentang dengan rumah-rumah berwarna coklat yang tersusun mirip rumah semut dan diselingi pepohonan yang menjulang.
This slideshow requires JavaScript.
Perhentian kami pertama adalah Khardung La. Seperti ‘La La La’ di cerita saya pada hari kedua, La berarti Mountain Pass. Khardung La adalah mountain pass tertinggi yang dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. India menobatkan Khardung La sebagai The Highest Motorable Road in the World, dengan tinggi 18,380 kaki atau 5,602 meter di atas permukaan laut (menurut Devil on Wheels tinggi sebenarnya adalah 17,582 kaki atau 5,359 meter). Dan menempati urutan ke 11 dari daftar di Devil on Wheels, satu nomor di bawah Chang La. Padahal Chang La ini disuarakan menjadi The Second Highest Motorable Road in the World setelah Khardung La.
Tapi, berita terakhir yang saya baca menyebutkan, kalau BRO (Border Roads Organisation – Satuan militer di India yang bertugas dalan pengembangan dan maintenance jalan di perbatasan India) baru saja meresmikan The New Highest Motorable Road in the World yaitu di Ladakh juga, Umling La dengan ketinggian 19,300 feet atau 5,883 meter di atas permukaan laut.
Dengan ketinggian segitu, saya masih ketemu beberapa orang yang ngegowes loh. Padahal beberapa menit beraktivitas (cuma jalan ke sana ke sini sama poto poto) di Khardung La, saya udah pusing karena gejala AMS. Gimana yang ikut Ladakh Marathon ya. Ngebayangin lari 42K keliling Ladakh, belum lagi ditambah Khardung La Challenge, Highest Ultra Marathon in the World, kategori lari dengan jarak 72K mendaki dari Khardung Village ke Khardung La baru turun terus sampai Leh. Sangaaaar.
Kami sampai di Khardung La sekitar jam 12.30. Jarak dari Leh sampai di Khardung La sekitar 40 kilometer dan seharusnya bisa ditempuh sekitar satu jam aja, apalagi dengan driver selincah Gyal. Tapi karena macet saat keluar dari Leh, dan sempat juga terhenti karena ada perbaikan jalan, perjalanan kami sampai Khardung La dari Leh memakan waktu dua jam lebih.
Ada Khardung La café yang tidak kami singgahi, karena sibuk poto poto dan begitu kami kerasa pusing, kami langsung minta ngelanjutin perjalanan biar dapet tempat dengan ketinggian yang lebih rendah.
This slideshow requires JavaScript.
Setelah dari Khardung La, kami beristirahat sebentar sekalian makan siang di salah satu tempat makan di Khardung Village. Saya pesan Rice and Daal, dan hot ginger tea with honey and lemon. Ini pertama saya makan Daal, dan lumayan ketagihan. Bentuknya sih agak agak gimana, dari kacang-kacangan dan berkuah warna hijau kecoklatan. Cara servingnya si daal ini dituang di atas nasi. Yosi yang pertama pesan, agak ragu buat ikut pesan. Ternyata enaaak.
Saya tahu Rina dan Yosi ini pasangan, tapi apa suami istri? Apa pacaran aja? Saya enggan nanya, eh malah Ikhsanul yang nanya duluan. Hahahaha. Dan tanggepan Rina, “Yosi, am I your girlfriend?” sambil ketawa iseng gangguin si Yosi. No, I’m not his girlfriend, nor his wife. But yes, we’re couple. Salah satu jawaban yang sudah saya prediksi. Lalu Rina balik bertanya, “So you guys are couple too?” Hahahaha. No! Lalu muncul obrolan trip bertiga tapi si Adityo gagal ikut trip. (Untuk kesekian kalinya si Adityo batal trip saya bahas lagi. Hmph)
This slideshow requires JavaScript.
Jam 3 sore kami melanjutkan perjalanan. Kata Gyal perjalanan masih jauh, sekitar 4-5 jam lagi. Tapi justru pemandangan menuju Turtuk ini yang luar biasa. Kami menyusuri Nubra Valley, sebuah padang pasir dengan gunung-gunung batu yang menjulang sungguh tinggi. Sesekali kami lihat pasir-pasir berputar terkena angin, seperti angin puting beliung, hanya beberapa detik sebelum pasir-pasir itu menyebar lalu hilang disapu angin.
Jalanan berkelok, Shyok River berwarna hijau pucat, kadang kebiruan, menemani sepanjang perjalanan ini. Shyok River adalah sungai hasil mencairnya Siachen Glacier. Dari sini lah sumber kehidupan penduduk yang tinggal di tepi sungai. Mulai dari Hunder dan Diskit, Skuru, Bogdang, termasuk Turtuk.
Kami melewati beberapa jembatan gantung besar, yang dijaga militer India. Beberapa pos kami berhenti, Gyal mengambil beberapa lembar ILP, meminjam passport kami untuk dicek oleh petugas yang berjaga di pos-pos itu. Beberapa pos Gyal hanya melambaikan tangan.
Perjalanan ke Turtuk bener-bener membuka mata saya. Sebuah pemandangan Himalaya yang sangat berbeda dengan yang kami tempuh sebelumnya. Warna bebatuan yang kelam, sesekali puncaknya tertutup salju, Sungai Shyok yang mengalir kencang, menambah kesan dingin dan suram. Tapi ini luar biasa. Sudah bukan seperti bumi yang saya kenal.
This slideshow requires JavaScript.
Ketika melewati Bogdang, ada yang menarik perhatian saya: penduduknya. Saya yakin, mereka bukan lagi Ladakhi. Dibandingkan Ladakhi, kulitnya lebih putih kemerahan, sesekali saya perhatikan, bola matanya lebih hijau atau coklat terang, bulu mata dan alisnya lebih tebal. Saya yakin mereka keturunan Pakistan.
Sudah dekat belum Turtuk? Tanya saya kepada Gyal. Katanya masih sekitar 1-2 jam lagi. Wew. Padahal udah mulai gelap. Pinginnya sampai di Turtuk sebelum gelap. Jadi bisa keliling desa itu dulu.
Dan kami sampai di Turtuk sekitar jam 8 malam, sudah gelap, dan desa ini hampir nggak ada penerangan apapun. Rumah-rumah yang kami lewati juga gelap, heran juga kenapa nggak ada lampu juga dari jendela-jendela rumah. Kami hanya mengandalkan lampu senter dari masing-masing HP kami.
Saya ingat, kami melewati jembatan besar untuk menuju penginapan. Penginapan pertama yang kami cek, jalannya jauuuuh dan menanjak dari tempat mobil kami diparkir. Ada dua kamar yang ditawarkan untuk kami. Satu kamar untuk dua orang dengan biaya per orangnya Rs. 700 sudah termasuk makan malam dan sarapan esok harinya. Saya sih no problem, karena dengan kondisi desa seperti itu, mau cari yang lebih mewah juga nggak bakal beda jauh. Si Ikhsanul mau liat beberapa penginapan hasil dia browing dulu. Yosi keberatan dengan bentuk penginapannya, dia mau cari yang lebih nyaman. Dan Rina ngikut aja.
Kami melanjutkan untuk melihat penginapan hasil Ikhsanul browsing, K2 Guest House (yang saya ketahui kemudian kalo K2 adalah sebutan lain untuk Mount Godfwin-Austen, puncak tertinggi di dunia setelah Mount Everest, yang ternyata bisa saya lihat dari Turtuk).
Tapi ternyata, K2 Guest House penuh. Pemiliknya keluar rumah dan menyambut kami, sekaligus meminta maaf tidak dapat menjamu. Tapi dia merekomendasikan penginapan lain di dekat situ, milik kawan dekatnya, dan dia jamin recommended. Sampailah kami di tempat kami bermalam hari itu, Mayar Guest House. Ada tiga kamar dan semuanya kosong. Saya dan Ikhsanul pilih kamar paling ujung dengan kamar mandi dalam. Penginapan ini mematok harga Rs. 500 per orang. Atau sekitar 100 ribu Rupiah. Murah ya? Untuk air panas, kami diminta membayar Rs. 100 per orang. Awalnya Yosi masih keberatan dengan penginapan ini. Alasannya dia mau cari penginapan yang lebih dekat dengan jalan raya, karena memang untuk mencapai penginapan ini kami harus mendaki lumayan jauh. Sedangkan Rina dan Yosi membawa masing-masing koper besar. Tapi karena saya dan Ikhsanul sudah menetapkan untuk beristirahat di sana, juga Rina yang setengah merengek karena dia udah kecapekan, akhirnya kami berempat memutuskan untuk bermalam di Mayar Guest House. Bahkan pemilik K2 Guest House ikut membantu membawakan ransel kami berdua beserta koper Rina dan Yosi. Duh baik banget.
Tak lama kami menata ransel di kamar kami, masuklah pemilik Mayar Guest House ini. Adalah seorang lelaki keturunan Pakistan, Guram Husein. Dia memasuki kamar kami. Dia bertanya kami dari mana. Kami jawab Indonesia. Dia bertanya lagi, “Muslim?” Kami mengiyakan. Raut mukanya berubah. Muncul senyum di wajahnya, dia lalu menjabat tangan kami lama. Saya masih ingat tatapan dan senyuman dia. Dia bilang dia juga muslim. Dia bercerita sekilas tentang bagaimana ayahnya dulu bercerita kepadanya, saat menunaikan ibadah haji, ayah Guram bertemu dengan banyak sekali muslim dari Indonesia. Dan Guram merasa beruntung dapat bertemu salah duanya. Tiba-tiba dia bilang, air panas untuk kami malam itu gratis! Gantian kami yang menyalaminya sambil senyum senyum.
Malam itu kami makan malam dengan rice with daal. Ada yang spesial dengan makan malam kami ini, lalapannya. Seger banget. Guram bercerita semua sayurannya dia ambil dari kebunnya sendiri. Seladanya, timunnya, tomat dan wortelnya. Saya paling suka dengan wortelnya. Manis dan seger. Ini sayuran paling seger yang pernah kami makan, termasuk Rina, terbukti dengan tanpa malu-malu dia curi tomat dari piring saya.
Published by Akbar Siddiq
Remember your game.
View all posts by Akbar Siddiq